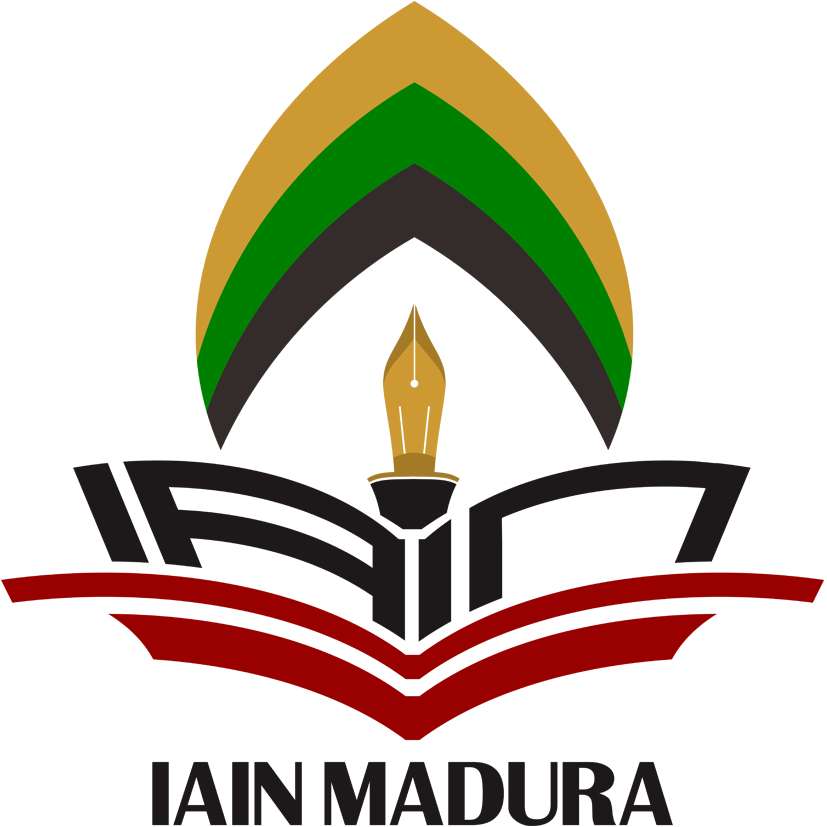PERKAWINAN ANAK DI MADURA: PERSPEKTIF BIMBINGAN KOSELING SOSIAL
- Diposting Oleh Admin Web Prodi BKPI
- Sabtu, 7 Oktober 2023
- Dilihat 1143 Kali
PERKAWINAN ANAK DI MADURA:
PERSPEKTIF BIMBINGAN KOSELING SOSIAL [1]
Fathol Haliq
Wakil Dekan 3 Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Tarbiyah IAIN Madura
Meretas perkawinan anak (pernikahan dini) di Madura merupakan hal yang kompleks. Kerumitan ini muncul dari masalah perkawinan yang bergelindan antara budaya, pelaksanaan dan regulasi. Ketiganya menjadi masalah yang seringkali muncul ketika ada masalah perkawinan anak. Pada aspek budaya diperlukan adanya data dan riset tentang perkawinan. Sedangkan dalam pelaksanaan perkawinan anak diperlukan adanya uraian lebih detail kerumitan kasus ini. Pada aspek regulasi berkaitan dengan kebijakan baik larang dan lainnya berkaitan dengan perkawinan anak. Dalam konteks ini membutuhkan kolaborasi antara akademisi, praktisi KUA utama Kepala KUA, penghulu, penyuluh, pemerintah.
Tulisan ini akan lebih mengedepankan sisi psikologis sebagai cara meretas perkawinan anak. Peretasan ini dianggap efektif dengan melihat dampak-dampak psikologis yang ada pada anak. Dampak psikologisnya terjadi pada kedua anak baik laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan. Kerentanan ini seharusnya dipikirkan tidak saja oleh orang tua anak juga pada sisi lain bagaimana konselor pernikahan memberikan wawasan atas bahaya seperti ini. Keraguan yang tidak bisa ditepis bahwa kesadaran akan bahaya memungkinkan setiap anak maupun orang tua untuk mencegahnya. Artikel ini hanya salah satu upaya dalam meretas kembali pernikahan anak sebagai komuditas rekreatif hiburan dan ekonomi di kalangan orang tua.
***
Anak merupakan usia yang rentan secara fisik dan psikologis. Secara fisik berkaitan dengan kerapuhan tubuh rangka individu pada anak yang belum kuat organ-organnya. Secara psikologis anak belum memiliki aspek psikologis yang sesuai dengan orang dewasa. Dalam hal ini usia yang seringkali dikedepankan berkaitan dengan anak yaitu 6-12 tahun. Usia 12 tahun sebenarnya merupakan awal dari remaja awal (Monks, 2006). Remaja awal pada dasarnya adalah usia anak yang sulit membedakan antara tugas dan kewajibannya. Di sini yang sama masih sangat bergantung pada orang tua dan kemandirian di sisi yang lain (Crain, 2007; Nurihsan, 2013). Artinya anak sangat tidak layak disandingkan dengan lawan jenis, baik laki-laki maupun perempuan.
Lutte pernah melakukan penelitian terhadap anak usia 10 tahun. Idealnya anak memiliki aktivitas dan interes yang bersama sesama anak. Ciri lainnya anak saling terbuka terhadap apa yang dibicarakan secara bersama-sama. Anak pada usia ini memiliki kecenderungan untuk saling melindungi yang menitik beratkan pada ketergantungan antara satu dengan lainnya. Anak pada usia ini sangat tergantung pada orang tua, terutama ibu. Ibu sebagai orang pertama yang diharapkan menjadi tumpuan bagi anak. Jadi ketergantungan anak pada orang tua menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan pada anak (Santrock, 2003; Sinaga, 2018).
Di samping itu, anak memiliki relasi yang dekat, kelekatan yang didasarkan keterbukaan, kehalusan rasa dan saling membantu. Ketiga relasi interaksional pada anak ini menjadi menarik, utamanya berkaitan dengan perkawinan anak. Anak akan menjadi dewasa sebelum waktunya karena sifat-sifat otentiknya akan hilang. Otentitas anak menjadikan mereka seperti buah matang sebelum waktunya. Biasanya sifat ini akan lebih memberikan ruang konflik yang terbuka baik pada relasi yang lebih dekat (primer) maupun terbuka (sekunder). Primer dalam rumah tangga itu sendiri, sementara pada tataran yang lebih terbuka akan melibatkan orang tua. Otentitas dan masalah inilah yang seringkali tidak pernah diperhatikan dalam perkawinan anak (Wangmo, 2015).
***
Sebenarnya tidak bisa dinafikan pula adanya beberapa upaya untuk mencegah sebelum terjadinya pernikahan anak atau di bawah umur. Antisipasinya sudah dilakukan oleh Kementeri Agama dengan batasan usia pernikahan sampai 19 tahun. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa anak boleh menikah baik laki-laki maupun perempuan jika berusia 19 tahun. Hal ini menarik karena kriteria 19 tahun dasarnya jika dilihat dari umur dan kedewasaan usia ini dianggap sebagai usia remaja akhir. Dimana usia remaja terpilah mulai usia 12-15 tahun masuk kategori remaja awal. Kategori tengah ada pada usia 16-19, sedangkan remaja akhir ada di usia 20-21 (Monks, 2006). Secara usia ini anak-anak telah berganti pada remaja dimana telah mempertimbangkan adanya kematangan fisik dan psikis pada remaja.
Mengapa pernikahan ini terjadi? Salah satu yang menarik adanya budaya masyarakat Madura yang berkaitan dengan tradisi ngalak tompangan (Hidayati, 2018). Dalam budaya dan tradisi ini sering terjadi karena peran orang tua, tokoh masyarakat mulai dari kiai sampai tradisi-tradisi dalam masyarakat. Ngalak tompangan sebagai bagian dari tradisi menggambarkan adanya keterlibatan masyarakat untuk berpartipasi dengan transaksional. Artinya hari ini membantu dan menyumbang serta mengembalikan ketika ada anak yang melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu upaya untuk mencegahnya dengan melibatkan semua pihak dengan penyadaran masalah utama dalam pernikahan di bawah umur ini.
Tradisi ngalak tompangan ini menimbulkan masalah lain. Misalnya adanya perubahan umur mulai dari klebun sampai pada pengadilan. Kedua peran institusi ini menjadi bagian penting bagaimana proses perkawinan anak tetap berlangsung ataupun tercegah sebelumnya. Peran klebun juga menjadi lapis kedua setelah orang tua (bapak/ibu) memiliki peran atas ini. Baik peran memuluskan maupun mencegah perkawinan anak. Peran ini memang dilematis karena bagaikan sesuatu yang bisa dilakukan maupun dicegah dengan kesadaran dan penyadaran dari diri sendiri dan sistem yang terjadi dalam masyarakat. Artinya meskipun telah dicoba untuk diantisipasi tetapi karena hanya dicegah di satu pintu, pintu yang lain tetap terbuka utamanya dalam meretas perkawinan anak.
***
Bagaimana upaya lain bisa dilakukan untuk mencari celah pencegahan perkawinan anak? Salah satunya dengan membuat sibuk pelaku pertama dalam perkawinan anak. Aktor dalam hal ini adalah anak dan orang tua. Penerimaan peserta didik mulai dari sekolah/madrasah menengah sampai perguruan tinggi hendaknya dipermudah. Dengan pelibatan dunia pendidikan dalam pencegahan ini diharapkan anak tidak lagi terjebak untuk melakukan pernikahan di bawah umur. Sementara kesempatan untuk masuk ke perguruan tinggi, utamanya di Madura hendaknya dibuka lebar yang tidak saja dilakukan dengan tes tapi juga non tes, misalnya jalur prestasi akademik dengan melihat kemampuan akademik dan non akademik, misalnya tanpa tes dan seterusnya. Upaya ini diharapkan tidak meningkatkan pernikahan anak di Madura.
Di samping itu, pencegahan lain harus ada upaya secara terus meneruskan untuk melakukan penyadaran utamanya orang tua dalam pencegahan masalah ini. Penyadaran ini bisa dilakukan secara langsung oleh para kiai dan penceramah serta penyuluh lapangan di KUA-KUA di Madura. Hal ini karena mereka dianggap tokoh masyarakat dan diikuti fatwa maupun saran-sarannya. Nasehat bagi orang Madura masih dianggap baik dan bagus jika disandarkan kepada tokoh masyarakat karena mereka memiliki rujukan yang jelas, utamanya berkaitan dengan hukum Islam.
Peran yang tidak bisa ditiadakan adanya penyuluhan dan bimbingan konseling sosial yang lebih komprehensif dengan melibatkan aktor dan tokoh di atas. Selain itu, Wallahu A’lam!
Rujukan
Crain, W. (2007). Teori Perkembangan. Pustaka Pelajar.
Hidayati, T. (2018). Ngala’ Tompangan: Perlawanan Perempuan terhadap Kawin Anak. Cahaya.
Monks, F. (2006). Psikologi Perkembangan. UGM Press.
Nurihsan, J. (2013). Dinamika Perkembangan Anak dan Remaja. Refika Aditama.
Santrock, J. (2003). Adolescence (Perkembangan Remaja). Erlangga.
Sinaga, J. D. (2018). Tingkat Dukungan Orang Tua Terhadap Belajar Siswa. Indonesian Journal of Educational Counseling, 2(1), 43–54. https://doi.org/10.30653/001.201821.19
Wangmo, K. (2015). The relationship between parents’ self-perceived family communication patterns, self-reported conflict management styles, and self-reported relationship satisfaction with their children in thimphu city, bhutan (Tesis). Bangkok University.
[1] Disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) PKM Penguatan Konseling Pra-Nikah untuk Mencegah Perkawinan di Bawah Umur pada Masyarakat Terpencil di Kabupaten Pamekasan, Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Mas Said Surakarta Jawa Tengah Sabtu, 2 September 2023 di Aula Pertemuan KUA Tlanakan Pamekasan